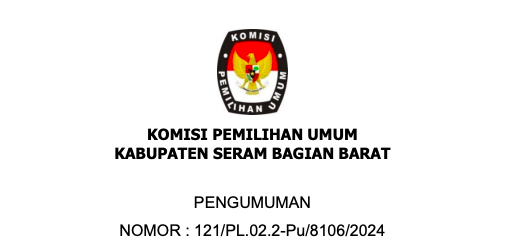Diskusi Pilkada di sejumlah daerah di Provinsi Maluku belakangan ini tereduksi soal siapa yang menjadi pejabat pengganti kepala daerah atau karteker. Alih-alih melanjutkan roda pemerintahan kedepan, dalam bayangan umum, posisi karteker dianggap sebagai simpul penting yang mengontrol sumber daya dan kemenangan kandidat di Pilkada. Peran karteker dianggap setara dengan petahana, karena memiliki diskresi politik untuk mendayagunakan kapasitasnya bagi kemenangan seorang kandidat di Pilkada.
Cara pandang yang demikian justru mengikis kontrol publik untuk menentukan pemimpin secara langsung di Pilkada. Peran publik seolah tidak berarti karena kemenangan kandidat bergantung pada intervensi politik karteker. Akibatnya, soal penting dari diskusi tentang siapa yang menjadi karteker bukan lagi terkait perannya untuk melanjutkan roda pemerintahan dua tahun kedepan, tetapi diarahkan pada diskresi yang ia miliki untuk memenangkan kandidat di Pilkada.
Tulisan ini bertujuan memberikan analisis alternatif bagi elit, aktivis dan publik di Maluku yang terkesan ikut-ikutan mempersempit Pilkada pada intervensi politik karteker. Pertama, selain tidak bermutu, diskusi tersebut juga mereduksi Pilkada sebagai arena tukar tambah kepentingan elit tanpa pelibatan partisipasi publik yang lebih luas.
Ada kencenderungan yang menganggap publik sebagai elemen tidak penting karena kemenangan kandidat lebih diarahkan pada keberpihakan politik karteker. Akibatnya, perluasan diskusi Pilkada di level publik menjadi macet karena terkunci sebatas pembicaraan di lingkaran elit.
Soal penting Pilkada bergeser pada “siapa yang menjadi karteker”, bukan “program penting apa yang bakal dilakukan dalam dua tahun kedepan”. Kedua, kecenderungan mengasosiasikan karteker sebagai “broker politik” bagi kandidat justru memperburuk proses demokrasi di aras lokal. Bayangan bahwa Pilkada akan memperluas demokratisasi di daerah karena mendekatkan masyarakat dengan pemimpinnya secara langsung dikacaukan oleh pengaturan kekuasaan yang terkunci di lingkar elit.
Elit tampak saling bersaing untuk me-lobby karteker demi mengamankan kandidat dan afiliasi politik yang ia dukung. Sialnya, aktivis dan publik juga merayakan kondisi yang sama dengan membela salah satu dari kelompok elit bertipe ini. Ketiga, ketergantungan publik atas karteker menunjukan lemahnya konsolidasi elit di akar rumput. Ketidak-mampuan ini menandakan lebarnya jarak antara elit dan masyarakat yang sejak lama tidak dijembatani.
Jarak tersebut mengisolasi publik dari agregasi kepentingan di Pilkada. Dibanding meyakinkan publik melalui program-program berkualitas di Pilkada, elit lebih tertarik mengambil jalan pintas untuk mengandalkan “intervensi politik” karteker. Dengan begitu, kontestasi di Pilkada terkesan ditujukan pada kapasitas karteker dalam mengorganisir dukungan, bukan pada kemampuan elit untuk menawarkan program-program bermutu.
Pertalian Demokrasi Karteker
Ketergantungan pada karteker bukan hal yang baru, melainkan bertalian dengan kebiasaan elit untuk memenangkan Pilkada melalui praktik-praktik pintas seperti : klientelisme politik. Praktik klientelisme kerapkali menempatkan aktor-aktor penting seperti raja/kepala desa, lembaga-lembaga adat/perangkat desa dan ASN sebagai broker politik para kandidat. Apalagi dalam konteks Maluku praktik klientelisme politik juga sangat kuat. Aspinall & Berenschot (2019:275) misalnya mencatat Indeks Persepsi Klientelisme di Maluku sebesar 6.06 dari rentang 3-7. Pilkada Maluku Tengah misalnya, praktik klientelisme berlangsung melalui kompromi personal maupun kooptasi politik langsung (Kelihu, 2021).
Melalui kompromi personal para penyedia dukungan seperti raja/lembaga adat/ASN turut berutang, bahkan tersandera dalam pertukaran politik yang dibangun dengan petahana. Apalagi petahana memiliki diskresi politik yang memungkinkannya untuk bisa menggunakan birokrasi dan insitutusi adat sebagai jejaring politiknya di Pilkada (Aspinall & Berenschot, 2019, Kelihu, 2021). Hari ini, jejaring klientelisme tidak saja digunakan untuk memenangkan Pilkada, melainkan juga dirawat untuk mendukung sanak keluarga secara bergantian. Dalam konteks Pilkada, kehadiran karteker sebagai penjabat pengganti kepala daerah, oleh beberapa pihak dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengorganisir birokrasi sebagai mesin politik di Pilkada. Selain buruk, asosiasi macam ini justru memotong rantai kontrol terhadap karteker.
Meski diusulkan ke Pemerintah Pusat, posisi karteker juga diperebutkan oleh setiap kandidat yang berkepentingan mencalonkan diri di Pilkada. Masa jabatan petahana yang terbatas dan sisa waktu dua tahun sebelum Pilkada adalah momen yang dimaksimalkan untuk membangun konsolidasi politik. Salah satunya dengan me-lobby karteker. Bagi petahana misalnya, dengan mengontrol karteker, ia lebih leluasa mengontrol jejaring klientelisme untuk memenangkan sanak kelurganya lagi di Pilkada. Sedangkan bagi kandidat non-petahana, karteker yang berpihak punya peluang yang sama mempermudah kemenanganannya untuk mengontrol birokrasi, aktor dan lembaga-lembaga adat (dalam konteks Maluku) sebagai penyedia dukungan.
Berbeda dengan petahana yang bisa saja memainkan jejaring lobby melalui pengusulan karteker oleh DPRD Kabupaten ke Kemendagri, elit non-petahana yang punya jalur lain untuk mengusulkan karteker melalui Gubernur. Bila pengusulan karteker diarahkan sesuai kepentingan politik, masing-masing elit akan saling berebut kepentingan melalui jejaring lobby tadi. Tidak menutup kemungkinan, dengan jejaring lobby yang berbeda setiap elit/kandidat berpretensi mengusulkan karteker sesuai kepentingan dan afiliasi politiknya di Pilkada. Terlepas perbedaan-perbedaan tersebut, kecenderungan umum yang tampak di dua kelompok elit (baik petahana dan non-petahana) adalah pertaruhan me-lloby karteker, dipandang sebagai langkah pintas untuk menopang proses kemenangan kandidat di Pilkada.
Minus Partisipasi Publik
Pertaruhan untuk menentukan karteker membuat Pilkada menjadi momen politik yang sangat bergantung pada polarisasi kepentingan elit. Berikut melemahkan partisipasi publik. Partisipasi publik diganti oleh kompromi politik elit yang berkepentingan mengkonsolidasikan kekuasaannya melalui saluran-saluran klientelistik. Salah satunya dengan mengorganisir pemenangan kandidat melalui intervensi politik karteker. Bukan tidak mungkin.
Akibatnya, Pilkada tidak dikanalisasi sebagai ruang demokratisasi yang mempertemukan kehendak publik dan elit, melainkan diatur oleh lobby-lobby elit yang pada gilirannya memobilisir publik ke dalam praktik-praktik klientelistik berbasis karteker. Persis di titik ini, peran karteker yang semula melanjutkan pemerintahan dengan dalih netralitas, justru rentan karena punya kemungkinan lain untuk bekerja sebagai struktur penyedia dukungan bagi kandidat.
Kuatnya konsentrasi kepentingan di lingakaran elit yang mendayagunakan karteker sebagai broker politik tidak saja menabrak etik publik, melainkan juga membuat sirkulasi kekuasaan menjadi sangat tertutup. Akibat ikutannya adalah : kontrol publik menjadi terbatas, dominasi elit semakin kuat dan kepentingan politik bakal tersumbat di level tengah : di level lobby dan kompetisi elit.
Pilkada pada akhirnya jadi arena politik yang hanya memfasilitasi imajinasi elit, tapi tidak berhasil mengadaptasi kondisi riil masyarakat. Apalagi menjadi arena negosiasi antara publik dan elit. Sialnya, terputusnya kanal-kanal politik antara elit dan publik tersebut justru diisi oleh klientelisme politik yang akut, kekuasaan keluarga yang menggurita dan kompromi politik jangka pendek yang tidak menyehatkan kritisisme publik (*).